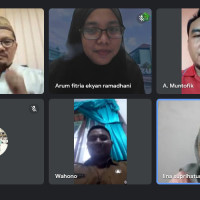(sumber foto: majalah.tempo.co)
Toleransi beragama, pada makna filosofis dan tindakan nyatanya, dalam banyak hal sesungguhnya adalah sebagaimana keberadaan Masjid Al-Hikmah dan Gereja Joyodiningratan di Surakarta yang berdiri bersebelahan. Jika Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal dibelah oleh jalanan di depan halaman masing-masing, maka Masjid Al Hikmah dan Gereja Joyodiningratan hanya dibatasi oleh tembok saja. Dengan kedekatan seperti itu, keduanya bahkan memakai alamat yang sama sebagai tengara tempat, yakni Jalan Gatot Subroto 222 Surakarta, tentu dengan iman yang tetap berbeda.
Iman yang berbeda tersebut telah berdampingan sejak Gereja Joyodiningratan berdiri pada tahun 1937, sepuluh tahun sebelum Masjid Al Hikmah didirikan. Keduanya menjadi afirmasi sederhana namun sarat makna: pada sebuah “rumah bersama” bernama toleransi beragama, perbedaan identitas agama itu sudah semestinya dapat berjalan beriringan sebagaimana adanya.
Seiring waktu, Masjid Al-Hikmah tidak kemudian melebur menjadi Gereja Joyodiningratan, demikian pula Gereja Joyodiningratan tidak berubah menjadi islami dengan berganti rupa menjadi Masjid Al-Hikmah. Keduanya tidak membangun niat dan kehendak untuk saling memengaruhi dan merubah warna keimanan.
Tentu saja tidak pernah mudah menjalani perbedaan tersebut dalam praktik sehari-hari, bahkan hanya dengan membayangkannya saja. Dalam hal berdampingan secara tempat, misalnya, bagaimana cara ikut merasakan sensitivitas kedua umat yang harus “berbagi” desibel suara atau bahkan keramaian interaksi umat saat menjalankan ibadah masing-masing secara bersamaan?
Ketika keberadaan dua lokasi ibadah hanya dipisahkan sebuah tembok pembatas, logika sederhana dapat menyimpulkan bahwa aktivitas kedua rumah ibadah untuk jamaah salat, do’a, kebaktian, pujian, dan nyanyian dapat serupa selang-seling suara dan mobilisasi warga yang sangat intensif dan interaktif. Bayangkan, bagaimana jika suasana khusyu’ mengaji Al-Qur’an tetiba harus mendengar nyanyian pujian yang berasal persis di sebelah bangunan tempat mengaji? Pun sebaliknya, dan rasanya masih banyak pertanyaan dilematis lainnya.
Menimbang segala hal tidak mudah demikian dan kenyataan masih guyubnya mereka kini, kedua pihak pasti sudah memilki kearifan bersama untuk saling menjaga dan menghindari masalah atau salah paham. Dalam kaitan demikian, kedua pihak selayaknya menjalankan prinsip dasar toleransi beragama, sebagaimana pandangan Buya Ahmad Syafii Ma’arif, tentang perlunya saling berlapang dada dan menghargai perbedaan. Segala perbedaan tersebut justru pada dasarnya mampu menjadi energi untuk berbuat kebaikan, bukan kerusakan.
Kedua tempat ibadah itu tetap berdampingan dengan merawat identitas keimanan masing-masing dan menerima perbedaan tanpa tergoda pada upaya-upaya untuk saling menyakiti iman dan keyakinan the others atau liyan. Inilah potret nyata perayaan kebersamaan dalam perbedaan, namun memerlukan upaya bersama untuk terus merawatnya. Pasalnya, merawat dan menjaga harmoni perbedaan, atau lebih jauh malah menekan prasangka keberagamaan, bukanlah sebuah upaya semudah membalik telapak tangan untuk mewujudkannya.
Merawat Toleransi
Pada sudut lain, apa yang dikenal sebagai upaya merawat kebersamaan dalam perbedaan tersebut terbukti tidak pernah mudah. Di derah Maluku Utara, sebagaimana menjadi bagian ekspose gerakan toleransi beragama bertajuk Sabang Merauke dan Islam Milenial beberapa waktu yang lalu, cerita tentang prasangka keberagamaan itu mesih jelas terlihat pada pandangan anak-anak yang berbeda agama. Pandangan demikian berakar dari konflik sosial tahun 1998 – 2001 di Halmahera dan Maluku.
Diceritakan, milenial yang lahir setelah terjadinya peristiwa tersebut begitu pandai menyampaikan persepsi negatif mereka terhadap umat beragama lainnya. Pada jawaban anak-anak tersebut, saat ditanya mengenai pandangan mereka tentang keberadaan sebaya pemeluk agama lain, terlihat betapa mereka memandangnya sebagai lawan dan musuh.
Dalam konteks lain, saat diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan sebebasnya mengenai agama selain yang mereka peluk, jawaban dari anak-anak tersebut juga penuh dengan prasangka. Mereka yang beragama Islam melihat temannya yang Katolik sebagai ancaman terhadap agama Islam, anak-anak yang beragama Protestan menilai Islam sebagai agama teroris, anak anak yang beragama Katolik menilai Islam agama yang angkuh dan memiliki acara tv show yang membahayakan, dan banyak cerita negatif lainnya.
Kemampuan bercerita negatif tersebut tentu bukan datang begitu saja dari pemikiran anak-anak yang relatif tidak rumit. Pemahaman tersebut lahir dari informasi salah yang didapatkan di tengah deras dan mudahnya arus informasi. Selain itu, pemahaman tersebut berasal dari bagaimana komunitas dewasa di sekeliling mereka yang membangun konstruksi kebencian dan prasangka terhadap pemeluk agama lainnya, karena banyak anak-anak tersebut yang belum lahir saat konflik terjadi.
Kebencian dan prasangka tersebut bahkan mewujud pada pembuatan garis pembatas pada tanah, sebuah demarkasi penegas antara “kami” dan “mereka”, atau jelasnya “kawan seiman” dan “lawan tidak seagama”. Artinya, dalam beberapa hal lingkungan dan komunitas di mana anak-anak itu berada tidak terlihat memiliki kehendak yang kuat untuk merawat dan melestarikan keberagaman.
Jika alamat Jalan Gatot Subroto 222 Surakarta adalah representasi dua agama yang memakai alamat yang sama untuk keberadaan mereka, kita juga mengenal banyak figur yang menyuarakan toleransi dan keberagaman tanpa lelah. Pada diri dan figur toleran seperti ini, peran dan tugas sebagai “alamat” bersama berbagai agama juga biasa difungsikan dan pemahaman bahwa menjaga toleransi adalah upaya tidak pernah usai. Salah satu figur tersebut adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikenal luas dengan ide humanisme dan toleransi beragamanya.
Meski sudah sedekade lebih Gus Dur wafat, ide dan pemikirannya mengenai toleransi beragama tetap relevan dan dapat memperkuat sisi “kerja” penguatan toleransi dan perlunya upaya untuk merawat keberagaman. Dalam dinamika keberagaman dan upaya menjaga toleransi, Presiden Joko Widodo sampai membayangkan, Gus Dur pasti geregetan dan kesal dengan indikasi dan fakta adanya kelompok yang meremehkan konstitusi, mengabaikan kemajemukan, bahkan berperilaku radikalistik (Kompas 24/12/2016).
Dalam kegelisahan tersebut, Presiden Jokowi sadar bahwa bangsa yang diberkahi kemajemukan ini tentu saja membutuhkan upaya bersama untuk merawat dan menjaga harmoni kebersamaan dalam perbedaan tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pandangan Gus Dur, toleransi bukan hanya soal menciptakan, namun juga merawatnya. Baginya, merawat toleransi sama halnya merupakan proses mendasar untuk menciptakan keharmonisan hubungan antarumat beragama.
Harmoni Masjid Al Hikmah-Gereja Joyodiningratan dan upaya merawat toleransi dalam program Sabang Merauke sesungguhnya adalah miniatur kondisi keberagaman dan upaya merawat tolerasni beragama di Indonesia beserta tantangan yang menyertainya. Beberapa gambaran perbedaan dan upaya merawat toleransi di atas sesungguhnya adalah cermin hal serupa di banyak tempat di Indonesia. Banyak tempat ibadah berbeda agama yang bersebelahan namun tetap saling menjunjung sikap saling menghormati. Namun demikian, sekali lagi, diperlukan kerelaaan dan kerja bersama untuk menjaga dan merawatnya.
- Saiful Maarif, Fungsional Asesor SDM Aparatur Ditjen Pendidikan Islam Kemenag -