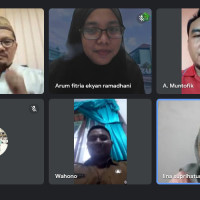Hari Buku Nasional (HBN) diperingati setiap 17 Mei. Tahun ini, peringatan HBN terasa sayup, hampir tanpa gebyar dan kemeriahan. Bisa jadi, hal ini karena masih dalam suasana lebaran. Pandemi Covid 19 juga tidak memungkinkan berbagai pihak untuk menggelar gebyar atau pameran buku sebagaimana biasanya.
Akan tetapi, kondisi ini tidak mengurangi makna dan peran penting buku. Buku masih menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif di sekolah, baik dalam bentuk cetak kertas maupun digital. Pada praktiknya, guru sangat terbantu dengan kehadiran buku karena akan memudahkan anak didik dalam memahami penjelasan mereka. Kehadiran buku makin penting di tengah proses pembelajaran daring selama pandemi.
Berjalan atau mandegnya pembelajaran tatap muka saat ini tidak juga mengurangi makna dan peran strategis buku. Pandangan demikian sejalan dengan beberapa temuan penting dalam beberapa dekade terakhir, jauh sebelum pandemi. Studi yang dilakukan terhadap hampir seribuan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Indonesia (Supriadi, 1997) mencatat bahwa tingkat kepemilikan siswa SD dan MI terhadap buku pelajaran berkorelasi positif dan signifikan terhadap hasil bejar yang ditempuhnya.
Temuan tesebut senapas dengan laporan World Bank yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku dan fasilitas lainnya berkorelasi erat dengan prestasi belajarnya (World Bank, 1989). Garis besarnya, semakin tinggi akses siswa terhadap buku pelajarannya, maka semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Oleh karenanya, setiap usaha untuk meningkatkan akses siswa terhadap buku pada dasarnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hasil belajarnya (A Taryadi, 1999).
Selain aspek korelasi buku terhadap hasil belajar siswa, hal mendasar lainnya adalah korelasi dan kontekstualitas buku dengan kebutuhan dan pengalaman diri siswa. Saat ini, yang ditunggu oleh para pemangku kepentingan lembaga pendidikan formal adalah buku yang disiapkan oleh guru sekolah mereka. Sebab, para guru inilah yang mengetahui kondisi riil kemampuan siswa, baik dari segi sosio geografis maupun intelektualnya. Dewasa ini, kalau diamati di dunia perbukuan, banyak buku yang ditulis jauh dari dunia realitas, bahkan terkadang keluar dari konteks.
Idealnya, guru, buku, dan siswa merupakan sebuah ekosistem yang saling membentuk dan memengaruhi. Dalam konsep ini, buku lahir dan berkembang dari rahim keseharian siswa di sekolah yang diolah oleh guru untuk menjadi sebuah buku yang pemanfataannya dikembalikan kepada para siswa.
Namun demikian, sayangnya, pada umumnya buku-buku tersebut lebih banyak karya orang lain, bukan karya guru mereka yang mengajar di sekolahnya. Hal ini disebabkan karena banyak guru yang tidak bisa membuat buku yang setara dengan buku yang diterbitkan oleh penerbit pada umumnya. Buku sebagai bahan ajar untuk anak didik masih dibuat oleh orang lain, termasuk para penerbit buku.
Kalau kita perhatikan, pada awalnya guru memang lahir ke dunia lebih dahulu ada daripada buku. Guru menjadi agen informasi dan keteladanan yang paling penting dalam proses pendidikan. Makin moderen sebuah bangsa berevolusi untuk menjadi makin maju, makin besar pula upaya untuk memasukkan buku menjadi elemen terpenting kedua. Secara evolusi, pendidikan untuk pembelajaran itu berawal dari guru baru ke buku.
Kita memimpikan setiap guru di sekolah punya karya tulis sendiri, sehingga kepala sekolah tidak perlu direpotkan lagi membeli buku untuk anak didiknya. Kepala sekolah cukup memfasilitasi proses kreatif dan upaya teknis menulis bagi guru di madrasah atau sekolahnya. Guru menjadi kreatif, kepala sekolah jadi inovatif. Praktek dan kondisi demikian juga bermanfaat secara karir dan lingkup administratif karena bisa dipergunakan untuk angka kredit kenaikan pangkat bagi guru berstatus PNS.
Dalam suasana pembelajaran saat ini, sebenarnya masyarakat selalu menunggu agar guru dapat membuat bahan ajar dan media pembelajaran sendiri. Harapannya, kondisi demikian pada akhirnya akan membuat harga buku menjadi murah dan memperluas keterjangkauannya. Dengan demikian, maka orang tua akhirnya akan mengeluarkan biaya pendidikan untuk anak-anaknya menjadi semakin efisien. Hingga saat ini, buku masih dianggap mahal bagi orang tua, apalagi jumlah buku yang harus dibeli biasanya banyak dan sudah ditentukan oleh sekolah. Belum lagi umur buku yang hanya seumur jagung. Kerap kali terjadi, ganti tahun ajaran, ganti pula bukunya.
Pemberdayaan Guru
Hingga kini buku pelajaran atau buku teks masih menjadi satu-satunya rujukan yang dibaca oleh siswa, bahkan juga oleh sebagian besar guru. Ini artinya, pada umumnya guru dan siswa akan menelan mentah-mentah setiap informasi yang terdapat di dalam buku pelajaran tersebut. Bahan lain seperti CD pembelajaran, perpustakaan, televisi, internet dan sejenisnya belum menjadi rujukan utama media pembelajaran siswa dan guru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi.
Masih sedikit kepala madrasah dan sekolah yang mampu memberdayakan guru-gurunya agar menulis buku untuk anak didik dan sekolahnya. Kepala sekolah lebih memilih dan mengadakan buku dari penerbit, alih-alih menimbang dan memberdayakan guru untuk menulis buku pelajaran. Terlebih lagi, buku dari penerbit kemungkinan menawarkan privilege di luar kepentingan dan substansi buku itu sendiri.
Masalahnya memang, ternyata menulis buku bagi kalangan guru kita masih dianggap sulit dan tidak menguntungkan. Budaya menulis kalangan guru kita masih rendah dibandingkan dengan budaya bicara atau ceramah. Oleh karena itu, diperlukan stimulan agar guru tertarik untuk menulis karya ilmiah.
Memang, guru PNS yang akan naik pangkat sudah "dipaksa" untuk menulis karya ilmiah yang bisa dibukukan. Guru PNS golongan III/c ke atas harus menulis karya ilmiah apabila ingin naik pangkat ke golongan yang lebih tinggi. Lebih jauh dari itu, guru PNS golongan IV/a harus membuat karya tulis ilmiah berbasis riset (Penelitian Tindakan Kelas) jika ingin mengajukan kenaikan pangkat ke IV/b. Kalau karya ilmiah ini tidak ada, jangan berharap bisa naik pangkat.
Kiranya, terdapat analogi yang relevan antara pendidikan dasar-menengah dan perguruan tinggi dalam hal ini. Di kalangan perguruan tinggi, dulu dikenal ada dosen yang “diktatorâ€. Para dosen ini, biasanya tidak muda lagi. Mereka punya "diktat" yang harus dibaca oleh mahasiswanya. Cara ini cukup efektif, karena memaksa dosen untuk menulis bahan kuliahnya, dan sang mahasiswa harus belajar lewat diktat yang telah disiapkan oleh fakultas. Biasanya, diktat ini lebih murah dari buku yang diterbitkan oleh penerbit umum.
Kita memerlukan guru yang mau dan mampu menulis buku sebagai bahan pembelajarannya. Dalam konteks global saat ini, telah terjadi perubahan yang terus menerus di mana peran guru dan buku akan tergeser oleh peran media lainnya, yakni pemanfaatan komputer dan internet. Peran guru memang masih diperlukan, karena guru punya kelebihan sebagai living agent. Sedangkan buku dan media lainnya, pada sisi lain adalah sumber belajar yang sangat statis. Dua kekuatan ini kalau harus memilih, mana yang menjadi prioritas? Tidak mudah untuk menentukan, karena kedua-duanya mempunyai nilai yang tidak dapat dipisahkan.
Di banyak negara, masih ditemukan guru sebagai satu-satunya faktor penentu prestasi ketika tidak ada resources lainnya. Di daerah pedalaman, peranan guru masih sangat dominan karena dia adalah sumber informasi dan ilmu pengetahuan, di samping simbol keteladanan. Guru masih menjadi sosok yang digugu dan ditiru (didengarkan dan diikuti). Namun demikian, hal ini tidak lagi berlaku di daerah perkotaan di mana sosok guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi dalam dunia pendidikan.
Buku adalah guru terbaik dalam dunia ilmu, dan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan prestasi dan prestise siswa. Untuk itu di kemudian hari diperlukan suatu kombinasi yang harmonis antara resources yang statis dengan resources yang hidup tadi. Kalau ada pameo yang mengatakan bahwa guru itu digugu (didengar) dan ditiru (diikuti), maka buku harusnya adalah pintu jendela dunia.
Lantas bagaimana kita dapat memberi makna bahwa guru dan buku merupakan aktor atau kekuatan yang memberi warna bagi dunia pendidikan Indonesia? Di sinilah tantangannya, yakni bagaimana menempatkan guru dan buku dalam perspektif yang lebih mulia, yaitu sebagai sarana untuk mewariskan ilmu pengetahuan, khasanah intelektual, dan peradaban manusia.
Jendela Kehidupan
Buku sesungguhnya merupakan media yang sangat penting dan strategis dalam dunia pendidikan. Keberadaan buku bisa dikatakan sebagai penafsir pertama dan utama dari visi dan misi sebuah pendidikan. Buku bisa dijadikan media untuk melakukan "jalan pintas" (by pass) dalam peningkatan mutu pendidikan dengan jalan mengeksplorasi lebih dalam topik-topik yang dibahas dalam buku tersebut.
Dalam masa pandemi Covid 19 ini, guru dituntut untuk mengembangkan sendiri media pembelajarannya. Untuk itu diperlukan suatu sinergi agar guru dapat menghasilkan buku yang bermutu, yang bukan hanya mencerdaskan, namun juga menggugah otak kita untuk menjadi lebih kreatif.
Kita sering menyamakan antara cerdas (smart) dengan pintar (intelligent). Buku yang kita perlukan bukan hanya melulu membuat orang cerdas, yang bukan hanya intelligent textbook (buku pintar), melainkan juga harus mindful textbook (buku yang menggugah otak) anak didik sebagai pembaca dan pengguna. Sedemikian penting buku dan daya gugahnya menjadi perhatian dalam proses pengembangan diri, filsuf Plato juga memberi tekanan tersendiri mengenai hal ini dalam bukunya, Phaedrus. Dikatakannya, buku akan melahirkan “pemberontak†kecil yang dalam dirinya akan melahirkan konsekuensi yang luas, bahkan bisa mewarnai dan menentukan jalan sejarah.
Plato mungkin "hanya" menganalogikan kekuatan teks dan buku dalam mitologi Raja Thamus dan Hermes, belum pada derajat level intelegensia manusia saat ini. Namun, filsuf Yunani tersebut selayaknya menekankan bahwa teks tertulis menjadi bukan semata-mata huruf-huruf yang mengalihkan pengetahuan dari guru ke murid, tetapi pemicu untuk penalaran kritis yang memungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh serta melembaga seperti sekarang.
Buku yang mindful adalah buku yang memberi banyak perspektif bagi anak untuk berpikir yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Buku tersebut juga dapat mengaitkan persepsi lingkungan yang dihadapi anak dan mendorong anak mampu mempersepsi solusi yang mungkin penting untuknya. Hal ini menjadi penting karena situtasi ini menjadi a novel situation, situasi yang senantiasa baru. Ini membuat para guru maupun siswa akan senantiasa merasa tercerahkan dengan situasi dan tantangan-tantangan baru yang menggoda nalar kita untuk selalu memperbaharui cara pandang kita terhadap siatuasi yang dirasakan atau diamati di lingkungan kita. Dan ini tentunya tidak mudah, sekalipun bukan mustahil.
Buku yang baik adalah buku yang mampu menggoda otak kita untuk berfikir dengan nalar yang dinamis. Ciri-ciri buku yang baik adalah yang bermakna, mendorong semangat belajar atau tidak belajar, menjadi perhatian, membangun kemandirian, dan punya makna untuk menemukan nilai.
Ketika seorang anak membaca sebuah buku, maka anak dipastikan akan dapat menangkap pesan dan makna yang terkandung (meaningful). Jangan sampai membaca lima halaman buku, namun tidak mendapat sense apa-apa. Sebuah buku yang baik harus mampu menjadikan anak bisa tahu makna dan hasil yang diharapkan.
Ketika seseorang membaca sebuah buku, diharapkan anak akan termotivasi untuk belajar tanpa harus dipaksakan oleh guru (motivational to learn). Karena buku adalah medium belajar, maka dia juga harus memuat motivational to unlearn. Pada saat sesuatu dipersepsi secara salah, maka buku pelajaran juga harus bicara salah. Buku harus berperan untuk mencopot hal-hal yang salah. Banyak pendapat umum yang beredar selama ini yang salah, dan buku harus mengatakan ini salah. Dengan begitu anak tidak lagi bertanya mana yang benar dan mana yang salah.
Buku yang baik adalah buku yang mendorong anak untuk memiliki atensi, perhatian, terhadap apa yang dia pelajari (keep attentive). Ini memang sulit. Tetapi ketika membaca Kho Ping Hoo atau Harry Potter misalnya, orang akan sulit untuk berhenti. Ada apa? Ada magnet attentive dimana penulis berhasil menanamkan kepada pembaca agar pembaca terus mengikuti apa yang akan disampaikan penulis.
Karena peran guru di kelas juga terbatas, maka buku harus bisa membantu atau mengisi kelemahan ini. Kalau buku-buku dikembangkan secara luas dengan self study, maka para siswa akan terbiasa untuk mengembangkan pola belajar yang mandiri.
Buku yang bermakna adanya buku yang mempunyai makna untuk menemukan nilai dan etika yang relevan dengan kehidupan kekinian dan moral yang berlaku. Tanpa hal ini, anak-anak akan menemukan hal-hal yang kontradiktif dalam dirinya. Kita harus saling melihat seluruh komponen pendidikan itu menyatu dan mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia ini.
Dengan kondisi tersebut, memang tidak mudah untuk menemukan buku yang bermakna dalam membangun kehidupan anak didik kita. Oleh karenanya, diperlukan suatu penyiapan situasi dan kondisi yang dinamis dan positif yang memungkinkan setiap guru dapat menyiapkan dunia sekolahnya dengan mandiri sesuai dengan kebutuhan dan tantangannya.
Pada akhirnya, buku adalah buku itu sendiri. Dia lahir sebagai daya gugah yang membangkitkan kesadaran dalam arus peradaban. Buku hadir untuk memberi dorongan dan memancing keingintahuan dalam bentuk membaca atau bahkan mengembangkan kemampuan menulis. Pada tahap pengkhidmatan buku sampai pada level demikian, kita mengenalnya sebagai, katakanlah akun personal (personal account) yang menginspirasi beragam kebaikan dan dorongan positif lainnya. Dengan posisi buku yang luhur seperti ini, merayakan momen peran dan kehadirannya tidaklah terutama tentang sebuah kemeriahan atau seremoni, karena pada dasarnya buku tidak pernah kehilangan perannya sebagai jendela kehidupan.
Wallahu a'lam.
Agus Sholeh, Kasubdit PAI pada SMP/SMPLB Direktorat PAI Ditjen Pendidikan Islam