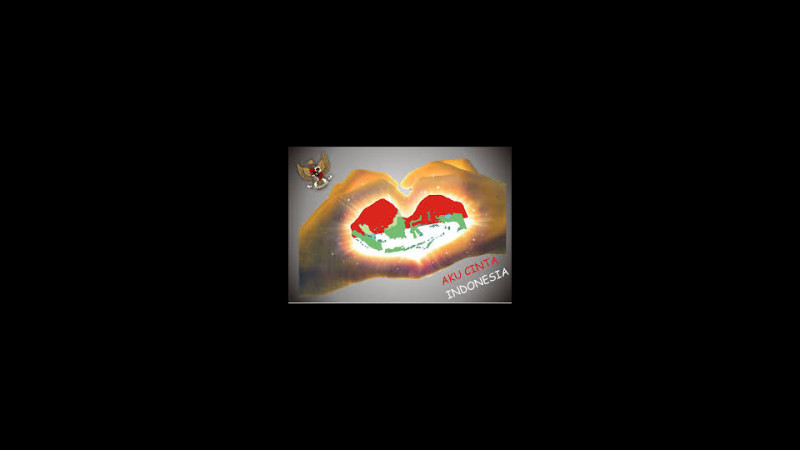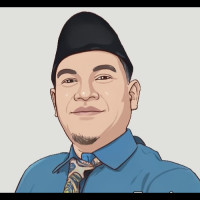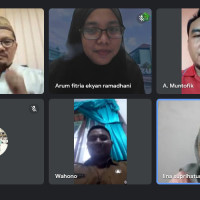Oleh: Nur Aghni Rizqiyah Baharawi
“Ada yang memar, kagum banggaku, malu membelenggu.
... ada yang runtuh, tamah ramahmu, beda teraniaya
Ada yang tumbuh, iri dengkimu, cinta pergi ke mana?”
-Efek Rumah Kaca
Bertahun-tahun duduk di Sekolah Dasar, saya selalu disuguhi kisah-kisah hebat para pejuang selama pelajaran sejarah. Dari sana saya mengetahui kalau ada di antara mereka mati, dibuang, diasingkan, dipenjara bertahun-tahun, dipisahkan dari keluarganya hanya karena menentang penindasan penjajah. Tapi, apa yang tidak begitu sampai masuk dalam logika saya, adalah untuk apa para pejuang itu melawan kalau, toh, mereka tidak digaji dari kegiatan itu? Malah perlawanan serupa itu lebih besar membawa marabahaya daripada manfaat kepada diri sendiri.
Tapi lama-lama saya mulai mengerti, kalau perlawanan dengan segala risiko itu lahir karena adanya satu cita-cita untuk hidup merdeka dari penjajah yang selalu memandang rendah masyarakat Indonesia. Para pahlawan itu pasti telah menyadari betapa besarnya bangsa ini, jika semua suku-suku bahu-membahu bersatu untuk menggapai satu cita-cita, maka bangsa ini pasti akan disegani dunia. Anggapan ini dapat dibuktikan dengan penggalan kalimat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana tertulis kalau kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus di seluruh dunia harus dihapuskan. Pada naskah UUD 1945 itu juga tertulis cita-cita Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Betapa besar dan mulianya cita-cita itu. Betapa bangganya para pahlawan jika mengetahui bangsa yang mereka perjuangkan dengan darahnya mampu mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Tetapi, jika kita mengumpakan sejarah bangsa ini sebagai perjalanan, kira-kira kita sudah sampai di mana? Apakah setelah 74 tahun merdeka kita telah mendekati cita-cita seperti yang tercantum dalam UUD 1945? Atau jangan-jangan kita tidak melangkah sedikitpun sehingga kita tidak berjalan ke mana-mana?
Belakangan ini, sementara presiden Joko Widodo sibuk mencari dana pembangunan di luar negeri, kita dikagetkan dengan pertikaian yang terjadi di Papua. Atau juga berita-berita tentang KPK yang mulai dilemahkan. Ini tentu satu kemunduran.
Di internet dan televisi kita melihat bagaimana kerusuhan di Papua terjadi hanya karena ada orang yang meneriaki orang Papua sebagai monyet. Satu perilaku yang kurang pantas rasanya. Dan menurut saya, wajar orang Papua marah dan turun ke jalan berdemonstrasi. Maka dari itu, seharusnya presiden turun ke lapangan dan menenangkan masyarakat di Papua sana. Minimal pelaku yang berteriak ‘monyet’ pada orang Papua itu disuruh oleh presiden untuk meminta maaf. Sedangkan soal KPK yang dilemahkan, saya belum sepenuhnya mengerti.
Bagi saya, KPK adalah satu-satunya benteng terakhir dari masyarakat sipil untuk memerangi pejabat negara yang suka menipu dan mencuri uang rakyat. KPK adalah lambang kejujuran, ketegasan, dan keberanian berbicara yang benar. Segala pelemahan pada KPK adalah bentuk penghianatan pada harapan untuk bersih dan jujur dalam kehidupan bernegara. Dan pelemahan terhadap KPK, bagi saya, adalah satu tanda kemunduran.
Hal-hal semacam ini sebenarnya persis batu penyandung yang menghambat kita berjalan ke tujuan. Kita sebenarnya sudah bisa mengurus bermacam-macam persoalan yang lebih terkait dengan pembangunan atau pemajuan kebudayaan. Tapi hanya karena mulut seorang yang tidak tahu adat, saudara-saudara kita di Papua sana sampai berteriak ingin memerdekakan diri. Dan tentu proses penyelesaian ini panjang dan memakan waktu. Barangkali pemerintah mesti segera menempatkan urusan Papua ini sebagai perhatian utamanya.
Begitu pula KPK. Bukan dilemahkan, seharusnya mereka diperkuat. Karena merekalah lembaga yang paling bisa diandalkan untuk memerangi korupsi dan penyelewengan uang negara. Kejahatan-kejahatan seperti itu tentu akan sangat mudah terjadi di era ketika Presiden Jokowi sedang mengupayakan pembangunan besar-besaran seperti sekarang ini. Contohnya, pemindahan ibukota ke Kalimantan, tentu itu akan memakan banyak dana. Kalau tidak diawasi, bisa-bisa pembangunan berjalan serampangan dan tidak tepat sasaran. Wilayah-wilayah lain di Indonesia juga masih menunggu pembangunan dari segala aspek, terutama aspek pendidikan dan kesehatan, agar ketika hendak melanjutkan kuliah atau berobat, orang-orang tidak perlu jauh-jauh berangkat ke Jawa sana.
Tetapi lagi-lagi, itu semua tidak akan selesai dengan baik kalau negara ini masih disibukkan dengan kasus-kasus ujaran kebencian, hoax, persekusi terhadap minoritas. Coba bayangkan jika para pahlawan yang wafat untuk negara ini hidup kembali dan menyaksikan apa yang kita perbuat, apa kita tidak malu di hadapan kebesaran dan keagungan nama-nama mereka? kita mestinya sadar, kalau berkontribusi pada pembangunan negara itu lebih mulia daripada menghayal dan bermimpi tentang kebesaran suatu kelompok agama atau ras tertentu, apalagi dengan menjelek-jelekkan agama atau ras saudara kita yang lain. Kalau memang kita bangsa yang besar, maka buktikan, bukan malah sibuk menjelek-jelekkan bangsa lain apalagi mencari musuh di antara sesama kita sendiri.
Akhirnya, kalau ramah-tamah, adat-isitiadat, sudah diabaikan. Lalu malah memupuk iri dan dengki, maka cinta pergi ke mana? Maka kita harus ke mana? Jika terus begini, kemuliaan cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tak lebih dari tulisan kusam di atas kertas. Cita-cita itu tidak menjadi kenyataan yang harus kita upayakan bersama-sama.