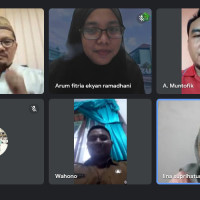Sumber foto: arosmarita.com
Novel berlatar tragedi Mei 1998 adalah Juara I Lomba Cerita Islam (Ceris) Siswa SMA/SMK tahun 2018 Direktorat Pendidikan Agama Islam.
Karya ini diangkat sebagai upaya menyegarkan program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Agama Islam dalam bidang literasi Pendidikan Agama Islam pada siswa.
Mengingat panjang dan durasi penulisan, novel akan dibagi menjadi beberapa bagian.
Novel ditulis oleh I'ir Hikmatul Choiro, Siswi SMAN 1 Krembung Sidoarjo Jawa Timur
Bagian 1:
Ranting Pertama yang Patah
“Cepat-cepat, mereka sedang menuju ke sini!â€
Kantor yang semula tenang menjadi bising. Beberapa orang berteriak. Bahkan supervisor yang duduk di depan Liana saat ini menginginkannya untuk segera pergi dari tempat itu.
“Mbak lebih baik sekarang pergi, keburu mereka datang ke sini! Kami akan menginformasikan hasil selanjutnya jika kondisi sudah kondusif!â€
Liana tanpa banyak bicara mengangguk. Perasaannya didera rasa takut. Dia mencangklong tasnya asal-asalan dan berlari keluar ruangan. Lift di ujung lorong penuh karena sudah banyak yang menggunakan.
Lorong-lorong pun ramai oleh manusia yang hilir mudik sibuk mencari keselamatan. Liana tidak kehabisan akal. Kakinya memutar jalan lain menuruni tangga. Beberapa langkah hampir saja dia jatuh keseimbangan saking paniknya.
Sepanjang menuruni tangga, bibirnya tak henti melafalkan doa. Liana memaksa kakinya untuk terus berlari meninggalkan gedung berlantai empat dan menuruni jalan raya. Telepon yang ada di dalam tasnya berdering berkali-kali, tapi Liana tidak punya banyak waktu untuk mengangkat. Sebab prioritas utamanya adalah segera menemukan angkutan umum dan pulang ke rumah.
Pemandangan pertama yang tertangkap netranya adalah betapa kacaunya kondisi di jalan raya membuat dirinya bergidik ngeri. Asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kejauhan. Sesekali terhirup dan membuat paru-parunya sesak. Jalanan sepi. Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang. Sementara keributan terlihat semakin jelas. Rupanya mereka sebentar lagi mendekati kantor.
Beberapa orang yang ikut berlari karena rasa takut. Semuanya berwajah kalut dan panik. Ekspresi mereka sama dengan Liana, merinding sekaligus ketakutan. Satu dua kendaraan yang lewat disetop dengan terburu dan berebut. Beruntung sebuah taksi melewatinya. Liana memasuki taksi dengan menghembuskan napas panjang.
Dering telepon yang kesekian kalinya baru bisa Liana jawab.
“Assalamualaikum, Ma!â€
“Liana!†suara ibunya di seberang berteriak khawatir. Sembari menelepon, Liana mengawasi keadaan sekitar. Miris. Jalan raya seperti arena medan perang. Banyak toko dan ruko yang dijarah. Kendaraan dibakar di tengah-tengah jalan. Benar-benar sepi dan tidak ada orang yang terlihat. Kemana mereka semua?
“Mama bagaimana di sana?†Liana bertanya, berdoa agar kedua orang tuanya baik-baik saja.
“Mama sedang mengepak barang. Papamu berjaga-jaga di luar. Mencoba mengamankan amukan massa.â€
Liana mengucap syukur kemudian.
“Liana akan segera sampai, Ma. Mama baik-baik saja ya sama Papa.â€
Meskipun hatinya sendiri diliputi takut dan ngeri karena beberapa kali dia melihat mayat-mayat yang bergelimpangan, Liana tetap berfikirkan positif. Memasuki jembatan, Liana terhenyak meyaksikan mayat-mayat perempuan berjejer tanpa busana dengan banyak darah berceceran.
Mereka mati sebab dibunuh dan dibakar.
“Pak, bisa lebih cepat sedikit?†Liana panik, takut-takut jika mereka bertemu rombongan massa yang disulut api amarah. Selang beberapa menit, taksi yang dia tumpangi berhenti.
“Ada apa, Pak?â€
“Anu itu..†sopir tua itu panik. Dua orang berbadan tegap sudah menghadang jalan. Mereka memaksa masuk.
“Pak jangan biarkan mereka masuk!†Liana menjerit.
Terlambat!
Kaca depan mobil sudah di hancurkan. Pak sopir tua semakin tidak kuasa ketika sebilah pisau teracung di lehernya. Mobil terbuka tanpa ada perlawanan.
Dua orang bertubuh tegap dengan cepat masuk ke dalam taksi. Liana gemetaran. Karena sebuah pistol juga ditodongkan ke kepalanya. Air matanya merbak. Pikiran positif yang beberapa lalu berada di otaknya kini tidak lagi muncul.
Liana tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya selanjutnya. Tapi yang jelas, sopir tua itu sempat diancam untuk terus melajukan taksi tanpa berhenti.
Liana kewalahan menghadapi dua orang lelaki yang sudah tertutup akal sehatnya dan melihatnya sebagai mangsa empuk sebagai sasaran sehingga berusaha menguasai tubuhnya.
Liana tidak bisa melawan. Kedua orang itu terlalu kuat untuk dia lawan sendirian. Sementara pak sopir dengan takut-takut menjalankan taksi dengan kecepatan sedang.
Kedua orang itu memperlakukannya dengan kasar. Hampir saja Liana hilang kesadaran kalau saja dua orang itu tidak berhenti menikmati tubuhnya dan meminta pak sopir menghentikan taksi.
Terhitung sembilan jam sampai akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan membanting pintu dengan keras, Liana kemudian merasakan sakit disekujur tubunya setelah dua orang itu pergi.
Rasanya seperti dia akan kehilangan nyawa jika penderitaan itu tidak juga berakhir.
Liana tidak bisa berhenti menangis. Ingatannya kabur pada kedua orang tuanya dan Kong, kekasih yang akan menikah dengannya minggu depan.
Pikirannya melayang pada gaun pernikahan yang sudah dia siapkan dan semua keperluan menikah yang sudah hampir sempurna.
Liana menangis, dia merasakan harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Impiannya untuk menikah dengan Kong hancur sudah.
Kini dia tidak lagi sempurna. Apa kata Kong nanti jika melihat dirinya yang seperti ini? Apa kata kedua orang tuanya apabila menyangsikan dirinya yang sehina ini?
Liana menanggis semakin kencang sampai tersedak-sedak. Hatinya hancur. Batinnya sakit. Begitu biadapnya para manusia itu hingga tega membuatnya seperti ini, merebut kebahagiaannya hanya dalam sehari.
Pak sopir tua menatap dengan penuh rasa bersalah.
“Maaf,†hanya itu kata yang terus keluar dari mulut pria itu. Liana bahkan tidak bisa mendengar ucapan ataupun suara yang ada di sekelilingnya dengan jelas.
Mendadak dunianya hening. Seperti sendirian di muka bumi. Liana sangat terluka.
Tubuhnya tidak berhenti bergetar karena gemetar. Rekaman jejak wajah kebengisan kedua orang itu ketika menjamah tubuhnya tidak pernah sekalipun dia lupa. Sangat jelas dan nyata.
“Maaf. Saya antar ke rumah sakit ya, Neng,†hanya itu yang bisa sopir itu lakukan. Tidak ada balasan dari Liana. Gadis itu terlalu shock dengan peristiwa yang baru saja menimpanya.
“Ayo Neng sudah sampai,â€
Taksi berhenti tepat di depan rumah sakit. Liana menggeleng.
Kesadarannya sedikit demi sedikit pulih. Tubuhnya masih terkapar di kursi penumpang. Dia sudah kembali berpakaian lengkap.
“Antar saya ke rumah.†Liana terbata-bata mengatakan itu.
Tenaganya sudah banyak tersedot untuk melawan. Tapi tetap saja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Liana menyalahkan diri karena dia gagal menyelamatkan kehormatannya dan menjadikannya seperti ini.
Mengingat itu Liana kembali menanggis. Pikirannya kacau. Sepanjang perjalanan Liana sedikit-sedikit selalu menangis jika teringat peristiwa beberapa jam yang lalu.
Matanya panas. Liana terus memaksakan diri untuk menangis meskipun tidak ada air mata yang keluar. Tidak tega melihat kondisi Liana yang benar-benar buruk, sopir tua itu tidak bisa memaksa Liana untuk masuk dan mendapatkan perawatan medis.
“Di mana rumahnya, Neng?â€
Liana tidak menjawab. Dia masih menangis. Sopir tua kembali dibuat bingung.
Dengan sungkan dia membuka tas Liana yang terlempar sampai di kursi depan setelah sebelumnya permisi mencari kartu nama atau identitas apapun yang bisa menunjukkan alamat rumah Liana.
Taksi berhenti. Liana keluar dengan tergopoh. Matanya mengerjap berkali-kali tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Rumah besar bertingkat itu hangus tak bersisa.
Dengan gemetar dan tidak percaya, Liana ingin menghubungi kedua orang tuanya. Liana meraba-raba saku bajunya, mencari telepon genggamnya. Kakinya lemas ketika tidak menemukan benda itu.
Bahkan di dalam tas yang diberikan sopir tua itu padanya juga tidak ada.
Ah! Dia ingat dua orang itu sempat membuang teleponnya dan mengancamnya.
“Kalau kamu lapor dan bilang ini pada keluargamu, tunggu saja. Aku akan membunuh semua keluargamu!â€
Liana benar-benar takut. Jika dia memberi tahu, orang tuanya akan dibunuh.
Tapi saat ini dia hanya ingin tahu kabar dari orang tuanya. Tidak mungkin mereka ikut hangus di dalam. Tidak mungkin!
Bagaimana ini? Tidak mungkin kedua orang tuanya meninggal kan?
“Mama! Papa!†Liana menjerit histeris. Dia ingin berlari ke dalam puing-puing bangunan yang menyisakan bara api kecil yang belum padam, tapi sopir tua itu dengan tanggap mencegahnya untuk masuk ke dalam.
Liana pasrah. Tubuhnya merosot ke tanah. Setelah apa yang dia lalui, apa orang tuanya juga berhak menerima ini semua?
Lihatlah, rumah itu benar-benar tak bersisa. Semua ludes. Termasuk toko kelontong di samping rumahnya. Jalanan sepi. Beberapa rumah tetangga juga bernasib sama.
Liana ingin masuk ke dalam, memastikan apakah orang tuanya benar-benar ada di dalam atau tidak. Berkali-kali sekelebat senyum mamanya menghias.
Membuat hati Liana semakin goyah. Perasaannya kacau balau. Otakknya tidak mampu berpikir secara rasional lagi.
“Neng jangan masuk ke sana, bahaya.
Nanti tertimpa kayu gosong.†Pak sopir juga tidak mau kalah dengan Liana yang terus mencoba untuk berlari ke arah reruntuhan bangunan. Liana tidak menggubris.
“Astagfirullah, ada apa ini?â€
Sopir tua itu menghembuskan napas lega melihat lelaki setengah baya menggenakan sarung dan peci menghampiri.
“Ah, ini Pak Haji, dia nekat mau masuk ke dalam sana untuk mencari kedua orang tuanya. Padahal itu sangat berbahaya.†Jawabnya.
“Sabar neng, sabar. Jangan gegabah. Bisa jadi kedua orang tuamu tidak ada di dalam sana.â€
lelaki yang ternyata Haji Abdullah, itu menengahi.
Liana mengenal orang itu. Dia memang haji terkenal yang ada di komplek kampungnya meskipun Liana hanya pernah bertemu dengannya sekilas.
Atau kadang ketika Haji Abdullah mengunjungi rumahnya, ada keperluan dengan bapaknya.
“Apa sudah coba kamu hubungi kedua orang tuamu?†Pak Haji bertanya lagi. Liana menggeleng.
Matanya perih karena terlalu banyak menangis.
Pak Haji menghela napas panjang. “Lebih baik kita coba untuk menghubunginya nanti.Daripada itu, apa kamu baik-baik saja?â€
Liana teringat kembali dengan peristiwa itu. Dia kembali menangis sesenggukan. Lututnya terlalu lemas untuk menopang berat badannya sendiri. Dirinya kembali terjatuh di tanah.
“Anu, pak haji,†Pak sopir takut takut menghampri Pak Haji dan membisikkan sesuatu. Pak Haji mengangguk mengerti.
“Liana,†diluar dugaan. Suara lembut Pak Haji membuatnya menoleh, “Mau ikut saya ke rumah?â€
Liana sedikit mundur. Haji Abdullah menampilkan senyum kebapakan, “Tidak apa-apa. Banyak orang-orang yang bernasib sama denganmu yang ada di rumah saya sekarang. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut saya ke rumah.â€
Liana kembali berpikir. Tapi melihat kesungguhan di wajah Pak Haji membuat Liana yakin.
Lagipula tidak ada tempat untuknya pulang. Rumah satu-satunya milik keluarganya terbakar. Dia tidak mungkin pulang ke rumah kerabatnya. Pada akhirnya Liana menyetujui ajakan Pak Haji untuk ikut ke rumahnya.
“Kita ke rumah sakit dulu tapi ya,†Pak Haji menoleh, “Bisa antarkan kami, Pak?†“Bisa, Pak Haji!â€
Benar kata Pak Haji, setelah diantar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, Liana menjumpai banyak wanita berkulit putih sepertinya yang sedang duduk-duduk di ruangan sempit berukuran 10 x 10 meter yang biasanya di gunakan untuk mengaji.
Aura mereka sama. Sama-sama kelam dan gelap. Satu dua diantara mereka menyambut kedatangan Liana dengan tatapan kosong. Kebanyakan dari mereka terluka. Bahkan ada yang mengalami luka parah sampai sekujur tubuhnya harus diperban.
“Assalamualaikum!â€
“Waalaikumsalam!†Seorang gadis lain keluar dari dalam rumah yang berseberangan dengan tempat untuk mengaji.
Wajahnya cantik dalam balutan jilbab merah muda. Liana sempat terpeson. Gadis itu mencium tangan Pak Haji dan tersenyum lebar.
“Ini Zahra, anakku!â€
Zahra mengulurkan tangan, Liana diam.
Gadis itu menarik tangannya kembali dan tersenyum canggung.
“Anaknya Cici Liem ya?†Zahra bertanya sekali lagi. Liana hanya mengangguk.
Siapa yang tidak mengetahui dirinya sebagai anak dari pemilik toko kelontong besar yang ada di kawasan komplek tempat mereka tinggal.
Tokonya juga cukup popular dan banyak pelanggan dari luar kompleks rumahnya.
“Abah, apa yang terjadi?†Zahra berseru ketika melihat luka perban yang ada di tangan Liana.
Itu luka yang Liana dapat sewaktu mencoba melawan dan akhirnya harus tergores pisau.
Liana sempat melihat Haji Abdullah meliriknya sekilas. “Terkena musibah.â€
“Asragfirullah!†Dikatakan demikian, Zahra langsung mengerti.
Sorot wajah gadis itu berubah menjadi raut sedih yang ditujukan untuk Liana.
Tiba-tiba Liana merasa jijik dengan dirinya sendiri.
“Bantu Liana ke kamar ya, Nduk1. Untuk sementara kedua orang tuanya masih belum bisa dihubungi. Nanti kamu pinjamkan telepon Abah pada Liana.â€
Zahra mengangguk mengerti. setelah mengatakan itu, abahnya pergi lagi.
Gadis itu turut berduka. Apalagi melihat wajah Liana yang kosong seperti kehilangan jiwa membuat gadis itu merasa sangat kasihan terhadap apa yang menimpa Liana. Zahra sebenarnya mengenal Liana.
Dulu sekali Zahra pernah berjumpa dengan Liana ketika ibunya menyuruhnya untuk berbelanja keperluan bulanan di toko kelontong milik orang tua Liana.
“Mari Ci, saya bantu.†Zahra memapah Liana hati-hati. Jika diperhatikan, selain luka di pegelangan tangannya, banyak lebam yang membiru dari kedua tangan dan kaki Liana.
Zarah mencoba memahami peristiwa yang baru saja menimpa Liana sama persis dialami oleh perempuan-perempuan di dalam, yang ditemukan abahnya.
Zahra mengizinkan Liana untuk menggunakan telepon rumah. Awalnya Liana ragu untuk menghubungi kedua orang tuanya.
Bagaimana kalau tidak ada sambungan di sana? Apa itu artinya kedua orang tuanya sudah meninggal dunia? Tapi kemudian dia menghembuskan napas panjang, mulai memencet nomor.
Lama Liana menunggu dengan gelisah, pada akhirnya dia bisa menghembuskan napas lega ketika suara wanita yang sangat dikenalnya itu menyapa telinga.
“Hallo,â€
“Mama?†Liana bertanya hati-hati.
“Liana anakku! Syukurlah. Kamu di mana, Nak?â€
Liana menatap sekeliling, Pak Haji diluar tengah berbincang-bincang dengan seorang
laki-laki.
Wartawan?
Tch, dia benci wartawan. Hati Liana sekarang penuh oleh kebencian.
Dia merapatkan tubuhnya pada dinding tembok, bersembunyi di balik sofa. Liana tidak mau bertemu wartawan atau siapapun itu. Dia tidak mau dirinya diekspos. Apalagi ancaman itu masih jelas terngiang di otaknya.
“Liana baik-baik saja, Ma. Liana ada di rumah teman. Liana tidak akan pulang sampai nanti keadaan sudah mereda.â€
Mungkin di telepon dia akan bersikap dewasa seperti tidak terjadi apa-apa.
Tapi tidak.
Jauh di lubuk hatinya, dirinya hancur berkeping-keping. Air matanya bahkan mengering.
“Loh kenapa? Mama sama Papa sekarang di Surabaya. Di rumah Paklikmu. Kamu tidak mau pulang kemari?â€
Liana menggeleng meskipun tidak ada yang melihat. “Ma, Liana pasti nyusul ke sana. Tapi sekarang Liana tidak bisa. Handphone Liana hilang. Nanti Liana kirimi surat.â€
Dia terus menyembunyikan kebohongan. Obrolan masih berlanjut.
Liana menjawab sepatah dua kata dengan pelan. Takut orang di luar mendengar suaranya. Mamanya bilang harta benda mereka ikut hangus terbakar.
Tapi beruntunglah mereka pindah tepat waktu sebelum rumah dibumi hanguskan.
Waktu terus bergulir.
Pepatah pernah mengatakan bahwa waktu akan menyembuhkan luka.
Tapi detik ini, luka itu tak kunjung sembuh. Justru yang ada akan semakin besar dan bernanah.
Trauma dan rasa benci sekaligus dendam tetap membara di hati Liana.
Mungkin Liana bisa lega kedua orang tuanya selamat. Tapi ada satu orang yang sangat dinantikan kabarnya oleh Liana. Kong.
Calon suaminya itu sama sekali tidak bisa dihubungi.
Padahal Liana sangat ingin mendengar suara lelaki itu.
Liana putus harapan.
Dua kemungkinan bahwa Kong tidaklah selamat dari peristiwa itu dan Kong pergi meninggalkan dirinya. Liana merasa kosong. Kehidupannya mati. Dunianya menjadi suram.
Lama-lama dia tidak kuat menghadapi dunia suramnya sendirian.
Liana berpikir, mungkin jika dirinya mati, maka rasa sakit dan penderitaan tidak akan dia rasakan lagi. Berbagai cara Liana coba, untuk memutus tali kehidupannya sendiri.
“Assalamualaikum, Ci! Waktunya makan!â€
Zahra masuk kamar dengan senyuman lebar.
Selama menginap di rumah Pak Haji, Liana harus berbagi tempat tidur dengan Zahra karena tidak ada lagi tempat kosong. Toh, gadis itu tidak merasa keberatan.
Zahra menghela napas panjang, sudah dua minggu Liana hanya duduk di tempat tidur kemudian menatap kosong ke arah tembok kamar, tanpa berniat beranjak untuk keluar.
Liana juga enggan melakukan aktivitas biasa. Bahkan dengan mandipun Liana enggan. Kadang Zahra harus telaten membantu Liana untuk mandi dan berganti pakaian.
“Aku tidak nafsu makan, Ra.†Balas Liana pendek. Semurung-murung dirinya, Liana masih nyambung diajak bicara oleh Zahra.
Zahra menyendok bubur hangat yang baru dimasaknya dan menyuapkan ke arah Liana.
Saat itu tanpa lama Liana menepis sendok yang diulurkan padanya dan membuang mangkok bubur yang dibuatkan Zahra.
“Aku kan bilang tidak mau makan!†Liana berteriak tanpa sadar.
Zahra dengan sigap membersihkan pecahan mangkok kaca yang berserakan.
“Astagfirullah, Ci. Jangan, Ci. Jangan!†Zahra kembali kerepotan karena Liana mengambil pecahan mangkok hendak mengiris tangannya.
“Ci, ingat. Tidak ada untungnya Cici mau bunuh diri. Allah akan murka pada hambanya yang mencoba mengakhiri hidup yang sudah ditentukan olehNya. Hidup mati itu takdir. Cici tidak bisa berbuat seperti ini.â€
Ditengah kepanikannya menenangkan Liana, Zahra tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada Liana. Gadis itu mendekap erat Liana yang masih tetap histeris.
“Aku benci dengan diriku sendiri, Ra! Aku benci! Aku jijik! Lebih baik aku mati!†Liana mencoba meraih kembali pecahan kaca yang sudah disingkirkan. Zahra menarik perempuan itu untuk mundur. Menjauhkan pecahan kaca dari jangkauan Liana.
“Lepaskan aku, Ra. Buat apa aku hidup? Masa depanku sudah hancur.
Aku tidak lagi utuh. Aku kotor! Bahkan Kong, calon suamiku tidak bisa dihubungi. Lebih baik aku mati!†Liana benar-benar buta akal. Hanya kematian menjadi jalan satu-satunya yang dia pikirkan untuk mengakhiri penderitaan hidup yang dia miliki.
“Ci, ada aku! Ada Abah! Ada saudara-saudara yang sama senasib dengan Cici. Tapi mereka berusaha untuk tabah. Mereka berusaha untuk menerima kenyataan. Mereka bahkan jauh lebih terluka.
Tapi mereka tetap ingin hidup.
Mereka ingin memulai hidup baru meskipun sangat sulit. Mereka berusaha! Zahra yakin Cici bisa! Bertahanlah, Ci. Jodoh hanya Allah yang menentukan. Allah tidak akan menguji hambaNya melebihi kemampuannya. Itulah kenapa Allah menguji Cici. Sebab Cici kuat.â€
Sembari mendekap, Zahra mencoba membisikkan kata-kata itu pada Liana. Liana agak tenang. Zahra merasakan air mata Liana menetes di tangannya.
“Yang perlu Cici lakukan hanya satu. Kembali pada Allah,†bisikan itu pelan.
Tapi menelusup dalam telinga Liana sampai ke dalam urat nadi. Air matanya menetes kembali.
“Ra, aku bukanlah wanita yang utuh dan suci seperti dulu lagi. Tapi apa Allah masih mau menerimaku?†Liana berbisik lirih.
“Masih, Ci. Masih. Allah menerima semua hambaNya selagi hambaNya mau bertaubat.â€
Liana tetap tidak habis pikir. Kenapa orang sebaik Pak Haji mau menolongnya?
“Kamu Islam kan?â€
Suatu waktu Pak Haji bertanya padanya. Dengan enggan Liana menjawab iya.
“Di dalam Islam diajarkan toleransi. Apalagi sesama muslim. Kita wajib membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Aku kenal betul dengan bapakmu. Beliau orang yang baik.â€
Liana menghela napas panjang. Dirinya yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu.
“Tapi mereka ada yang tidak muslim, Pak Haji.†Liana melirik wanita-wanita yang bernasib sama dengannya.
Mereka sedang berlajar membuat kerajinan, di ajarkan oleh Zahra. “Massa itu juga ada yang muslim.
Tapi mereka dengan ganas saling membunuh.†Tambahnya.
Pak Haji tersenyum, “Liana, masyarakat itu kompleks. Tidak satu agamapun yang memperbolehkan pembunuhan sadis atau brutal seperti itu. Demikian juga tak ada satupun ayat dalam al Qur-an yang mengajarkan kebencian terhadap orang lain.
Hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., dengan mulianya Rasulullah, yang selalu bersikap lembut terhadap siapapun, sekalipun terhadap orang yang memusuhinya.
Rasulullah selalu membalasnya dengan kebaikan. Bahkan sebagai seorang pemimpin beliau memberikan hak yang sama terhadap rakyatnya yang berbeda-beda agama, multikultural dan multietnis.
Sebab itulah Allah mengutus Muhammad sebagai Rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firmanNya:
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.†(QS. al Anbiya’ ayat 107)
Pak Haji menghela napas panjang, “Dalam kasus ini bukan sebab agama, Lia. Melainkan rasa serakah dan rasa tidak suka yang berlebihan hingga menjadi benci. Indonesia kan berazas pancasila, kamu, saya, semua orang di negeri ini adalah Indonesia. Tidak ada Pribumi dan Cina. Semuanya Indonesia.â€
“Bukan perkara yang mudah mendapatkan ideologi hingga dapat terpegang teguh seperti sekarang ini. Para pejuang dan ulama dulu saling merumuskan sampai pada akhirnya terwujudlah negeri yang berasazkan Pancasila ini. Bukan negeri yang berasazkan syari’at Islam, meski para ulama (cendikiawan Muslim) mempunyai andil besar dalam hal tersebut.†Sambungnya.
Mendengar itu Liana seolah sedang bersama kakeknya.
Bedanya jika Pak Haji akan mengaitkan sejarah dengan Islam, kakeknya tidak. Liana ingat betul kakeknya sering sekali menceritakan sejarah berdirinya Indonesia.
Dan kata-kata yang Liana selalu ingat adalah, “Kamu memang keturunan Tionghoa dan Jawa, tapi kamu lahir di Indonesia. Besar di Indonesia. Maka matipun kamu ada di Indonesia. Karena inilah rumahmu dengan Islam agamamu, Liana.â€
Zahra benar. Ada orang yang akan selalu menyayanginya dan akan selalu mendukungnya.
Keluarga barunya.
Sebulan Liana menetap di rumah Haji Abdullah, berangsung-angsur dirinya mulai membaik. Berkat Zahra juga yang mau menjadi sahabatnya untuk berkeluh kesah. Sedihnya semakin berkurang. Gadis itu selalu mengingatkannya untuk terus menjalankan ibadah.
Dilain sisi, dirinya merasa berat hati karena satu persatu wanita korban yang sama dengannya itu memilih meninggalkan rumah Pak Haji dan berniat melanjutkan hidup di luar
negeri. Mereka jugalah alasan yang membuat dirinya kuat. Liana sendiri yang menyaksikan proses mereka untuk bangkit. Salah satunya yang dilakukan Mei.
Wanita seumuran dengannya yang mengalami kekerasan seksual cukup parah. Wanita itu harus rela kehilangan payudaranya saat peristiwa itu terjadi. Tapi lihatlah, wanita itu kini menjadi kuat.
“Kamu yakin mau ke Singapore?†Liana ikut mengemasi barang milik Mei ke dalam koper.
Jika Mei pergi, resmi sudah hanya tinggal dia seorang diri yang akan menjadi benalu dalam rumah Pak Haji.
Mei tersenyum cerah.
Tidak seperti saat pertama kali Liana melihat Mei ketika wanita itu duduk dengan tampilan berantakan dan padangan kosong serta banyak perban yang membalut tubuhnya.
“Iya Lin. Aku takut hidup di sini. Memang tidak semua orang di sini jahat. Tapi aku masih trauma. Aku mau membuka hidup baru di sana.†selang beberapa menit, terlihat Zahra memasuki kamar Mei, mengulurkan sesuatu.
“Ci ini tiket, paspor dan kelengkapan lainnya yang sudah diuruskan Abah.†Mei menerima dengan senyuman lebar.
“Maksih, Ra. Makasih banget. Aku tidak tahu kalau saja aku tidak ditolong Pak Haji, jadi apa aku nantinya. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Terutama dengan kamu juga yang mau memberikanku semangat untuk terus melanjutkan hidup,†Mei memeluk Zahra singkat.
“Sama-sama Ci. Semoga kehidupan Cici di sana akan semakin baik. Cici jangan lupakan saya yah.â€
“Jangan lupakan aku juga Mei.†Liana menimpali.
“Tidak Lin. Bagiku kamu ini orang yang paling kuat.
Aku doakan segera ada kabar dari calon suamimu,†Liana menangguk. Dirinya tidak lagi berharap lebih. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Jika memang Kong masih hidup dan jodohnya, dia akan kembali pada dirinya. Tetapi jika Kong sudah meninggal, dia berdoa agar Kong diberikan tempat terbaik di atas sana.
Dua minggu setelah kepergian Mei, Liana semakin merasa tidak enak harus terus menerus merepotkan Haji Abdullah dan Zahra. Meskipun tidak sepenuhnya traumanya sembuh, setidaknya dia sekarang lebih bisa berfikir dengan waras.
Dia tidak akan sebodoh dulu lagi untuk mengakhiri hidupnya. Apalagi sekarang ini, dia tidak hanya membawa satu nyawa. Melainkan dua nyawa.
Astagfirullah, Liana mengusap wajahnya teringat akan pikiran gilanya dulu.
Ya! Liana hamil.
Ketika mengetahui berita kehamilannya, separuh hatinya sangat tidak rela membesarkan anak dari orang-orang biadap yang sudah merenggut kehormatannya. Tapi separuh hatinya tergerak untuk membesarkan anak itu bagaimanapun caranya.
Kali ini Allah kembali membukakan jalan untuk dirinya. Liana mendapat kabar dari kerabat dekat Kong. Lelaki itu ternyata mengalami musibah peristiwa itu da tidak selamat. Liana kembali diguncang kesedihan. Dia pernah berfikir bahwa Kong membuangnya. Tapi ternyata lelaki itu mengalami hal yang jauh lebih buruk dari dirinya. Kehilangan hak untuk hidup.
Liana merasa sangat bersalah.
Kesedihan yang berkali-kali menimpa dirinya membuat dirinya semakin kuat.
Liana tidak berlarut-larut atas kepergian Kong. Sebab tekadnya untuk memulai hidup sudah mantap. Dia tidak akan membiarkan kesedihan membuat semangat hidupnya hilang kembali. Karena kali ini dia sudah menemukan alasannya untuk hidup.
Bismillah!
Pada akhirnya Liana harus pulang. Apapun yang akan terjadi nanti, Liana mantap akan menghadapinya dengan sekuat hati.
Sebelum itu dia juga sudah mengatakan hal itu pada Pak Haji dan Zahra. Mereka merasa sedih tapi sangat mendukung usaha Liana.
“Hati-hati, Ci.†Zahra ikut mengantar kepergian Liana dengan kereta api. Gadis berjilbab itu memeluk Liana singkat.
Selalu ada perpisahan dalam sebuah pertemuan bukan? Selama ini Liana juga sudah menganggap Haji Abdullah dan Zahra sebagai keluarganya sendiri. Berat sekali meninggalkan mereka. Tapi apa mau di kata. Keluarganya juga sudah menunggunya.
Sejauh-jauhnya dia pergi, tetap rumah dan orang tua adalah tujuan utama.
Liana rindu dengan senyuman mamanya. Liana rindu, dengan suara papanya yang kadang-kadang selalu memarahinya dengan nada menaik beberapa oktaf.
Kepulangannya bukan hanya secara fisik, tapi hati, jiwa, pandangan hidupnya ikut berpulang kepada Allah.
Liana terpesona dengan pemandangan hijau sawah dari balik jendela kereta. Ternyata, ranting yang patah itu perlahan-lahan mulai utuh kembali.